Anak Jalanan dan Subkultur:
Sebuah Pemikiran Awal
Oleh Kirik Ertanto
Dalam kesempatan ini, kita akan mempercakapkan gagasan mengenai subkultur. Seperti kita kenali bersama, tema ini salah satu yang diabaikan dalam perbincangan mengenai masyarakat Indonesia modern. Untuk itu sejak awal saya ingin berterus terang bahwa apa yang saja sajikan masih menyentuh bagian-bagian pinggirnya saja. Subjek yang saya pilih dalam percakapan kali ini adalah kehidupan sebagian kalangan anak muda yang berada di jalanan. Dalam kata lain, melihat kehidupan anak muda di jalan sebagai satu subkultur.
Sebuah subkultur selalu hadir dalam ruang dan waktu tertentu, ia bukanlah satu gejala yang lahir begitu saja. Kehadirannya akan saling kait mengkait dengan peristiwa-peristiwa lain yang menjadi konteksnya. Untuk memudahkan kita memahami gagAsan mengenai subkultur anak muda jalanan, maka saya akan memulai dengan satu upaya membuat peta antara hubungan anak muda dan orang tua serta kultur dominan sebagai kerangkanya.
Sekurang-kurangnya ada dua pihak yang -berkat dukungan modal yang melekat pada dirinya- berupaya mengontrol kehidupan kaum muda, yaitu negara dan industri berskala besar. Di Indonesia, pihak pertama yaitu negara berupaya mengontrol kehidupan anak muda melalui keluarga. Keluarga dijadikan agen oleh negara untuk sebagai saluran untuk melanggengkan kekuasaan.
Melalui UU No. 10/1992 diambil satu keputusan yang menjadikan keluarga sebagai alat untuk mensukseskan pembangunan. Keluarga tidak hanya dipandang hanya memiliki fungsi reproduktif dan sosial melainkan juga fungsi ekonomi produktif. Pengambilan keputusan keluarga dijadikan alat untuk mensukseskan pembangunan pada gilirannya membawa perubahan pada posisi anak-anak da.n kaum muda dalam masyarakat.
Anak-anak dan kaum muda dipandang sebagai satu aset nasional yang berharga. Oleh karena itu investasi untuk menghasilkan peningkatan modal manusia (human capital) harus sudah disiapkan sejak sedini mungkin. Dalam hal tugas orang dewasa adalah melakukan penyiapan-peyiapan agar seorang anak bisa melalui masa transisinya menuju dewasa. Akibatnya ada pemisahan yang jelas antara masa anak-anak dan masa muda dengan masa dewasa. Adalah tugas orang tua untuk memberikan pemenuhan gizi yang dibutuhkan, mengirim ke sekolah sebagai bagian dari penyiapan masa transisi.
Saya Shiraishi (1995) yang banyak mengamati kehidupan keluasga dan masa kanak-kanak dalam masyarakat Indonesia mutakhir mengatakan bahwa implikasi lebih lanjut dari gagasan keluarga modern itu pada akhirnya menempatkan anak-anak sepenuhnya dibawah kontrol orang tua. Orang tua menjadi kuatir bila anaknya tidak mampu melewati masa transisi dengan baik, misalnya putus sekolah, dan akan terlempar menjadi kaum “TUNA” (tuna wisma, tuna susila dan tuna lainnya), kaum yang kehidupannya ada di jalanan. Kekuatiran ini bisa dilihat secara jelas dengan streotipe mengenai kehidupanjalanan sebagai kehidupan “liar”.
Bukanlah satu hal yang mengada-ada bila kemudian para. orang tua lebih memilih untuk memperpanjang proteksi anak-anaknya untuk berada di dalam rumah sebab lingkungan di luar rumah dianggap sebagai”liar” dan mengancam masa depan anaknya. Pilihan untuk memperpanjang masa proteksi anak-anak inilah yang kemudian ditangkap sebagai peluang dagang oleh para pengusaha.
Belakangan ini dengan mudah kita bisa melihat berbagai produk atau media untuk membantu penyiapan masa transisi anak-anak. Program televisi yang jelas menggunakan kata (televisi) PENDIDIKAN INDONESIA adalah salah satu contoh terbaiknya. Selain itu berbagai media cetak juga mengeluarkan berbagai produk bagaimana menyiapkan anak secara “baik dan benar” dalam rangka pengembangan sumber daya pembangunan. Para orang tua pada. gilirannya akan lebih mengacu pada berbagai media itu sendiri dibandingkan pada peristiwa sehari-hari yang dialami oleh anaknya.
Cara membesarkan anak yang diimajinasikan oleh negara dan pemilik modal inilah yang kemudian menjadi wacana penguasa (master discourse) untuk anak-anak Indonesia. Ia digunakan sebagai alat untuk menilai kehidupan keseluruhan anak dan kaum muda di Indonesia. Hasilnya seperti yang ditunjukkan Murray (1994) adalah mitos kaum marjinal:
yang dari sudut pandang orang luar menggambarkan orang-orang ini sebagai massa marjinal yang melimpah ruah jumlahnya dengan budaya kemiskinan dan sebagai lingkungan liar, kejam dan kotor … sumber pelacuran, kejahatan dan ketidakamanan.
Murray tidaklah sendirian dalam memberikan adanya dikotomi rumah dan jalan. Studi Siegel (1986), Saya Shiraishi (1990) dan Jerat Budaya (1998) menunjukkan temuan yang sama.
Studi Marquez ( 1998) mengenai kaum muda jalanan di Caracas menunjukkan bahwa anak muda itu tidak secara pasif menerima begitu saja pandangan negatif dari luar. Jalan raya bukanlah sekedar tempat untuk bertahan hidup. Bagi kaum muda tersebut jalanan juga arena untuk menciptakan satu organisasi sosial, akumulasi pengetahuan dan rumusan strategi untuk keberadaaan eksistensinya. Artinya ia juga berupaya melakukan penghindaran atau melawan pengontrolan dari pihak lain.
Bertolak dari gambaran sekilas di atas, saya akan menempatkan percakapan mengenai subkultur anak jalanan di Indonesia dalam titik potong antara dikotomi rumah dan jalan di satu sisi dan orang tua (kaum dewasa) dengan anak muda di sisi lain. Fokus dari percakapan kali ini untuk sementara saya batasi bagaimana corak mode kehidupan yang ditampilkan oleh kaum muda yang besar di jalan yang kemudian bertumbuh menjadi subkultur.
Meninggalkan Rumah, Menanggalkan Masa Lalu
Sebuah sebuah kategori sosial, anak jalanan bukanlah satu kelompok yang homogen. Sekurang-kurangnya ia bisa dipilah ke dalam dua kelompok yaitu anak yang bekerja di jalan dan anak yang hidup di jalan. Perbedaan diantaranya ditentukan berdasarkan kontak dengan keluarganya. Anak yang bekerja di jalan masih memiliki kontak dengan orang tua sedangkan anak yang hidup di jalan sudah putus hubungan dengan orang tua. Dalam tulisan ini, anak jalanan mengacu pada kategori anak yang hidup di jalan.
Seorang anak jalanan yang sudah hampir dua puluh tahun hidup di jalan menuturkan pengalamannya pergi dari rumah. Katanya waktu kecil ia banyak ngeluyur dibanding sekolah, lebih banyak bermain dari pada belajar. Akibatnya, teman-temannya sudah naik ke kelas tiga ia masih saja duduk dibangku kelas satu. Buat sebagian anak pergi ke sekolah tidaklah selalu berarti pengalaman yang menyenangkan. Seorang anak lain N bila mengingat sekolah maka yang muncul adalah gurunya yang galak dan tubuhnya yang menjadi sasaran sabetan. Katanya:
Waktu saya sekolah saya digebugin karena di sekolah saya goblog. Di bawa ke kantor karena.sering nonton Th lalu disuruh membaca di papan tulis tidak bisa. Di sabet badanku. Pak guru saya galak. Lalu saya keluar kelas tiga.
Keadan murid-murid bermasalah seperti itu biasanya dilaporkan oleh guru kepada orang tua murid. Laporan itu bisa menjadi penyulut kemarahan orang tua. Seperti yang dituturkan H:
dan pak guru saya sering datang menemui orang tua saya menceritakan keadaan saya. Saya dimarahi bapak tidak hanya dengan suara tetapi juga digebugi pakai sapu lidi sampai merah kaki saya
Berbagai penyuluhan, berita TV dan radio secara bertubi-tubi telah mengajar para orang tua memlaui pembatinan bahwa anak yang baik adalah anak sekolahan. Karena itu wajar saja bila guru tidak mampu lagi mendidik anaknya, maka orang tualah yang akan meng(H)ajar anaknya. Hasilnya seperti H dan N lari meninggalkan rumah.
Ketika pertama kali hadir di jalan, seorang anak menjadi anonim. Ia tidak mengenal dan dikenal oleh siapapun. Selain itu juga ada perasan kuatir bila orang lain mengetahui siapa dirinya. Tidaklah mengherankan bila strategi yang kemudian digunakan adalah dengan menganti nama. Hampir semua anak yang saya kenal mengganti nama. Hal ini dilakukan untuk menjaga jarak dengan masa lalunya sekaligus masuk dalam masa kekiniannya.
Anak-anak mulai memasuki dunia jalanan dengan nama barunya. Anak-anak yang berasal dari daerah pedesaan menggganti dengan nama-nama yang dianggap sebagai nama “modern” yang diambil dari bintang sinotren atau yang yang biasa didengarnya misalnya dengan anam Andi, Roy dan semacamnya. Seorang anak yang bernama Mohammad kemudian mengganti namanya menjadi Roni. Alasan yang diberikan karena Mohammad adalah nama nabi. Nama itu tidak cocok dengan kehidupan di jalan. karena yang dilakukan di jalan banyak tindakan haram.
Proses penggantian sebutan itu dengan sendirinya menunjukkan bahwa ia bukan sekedar pergantian panggilan saja tetapi juga sebagai sarana menanggalkan masa lalunya. Artinya ia dalah bagian dari proses untuk memasuki satu dunia (tafsir) baru. Sebuah kehidupan yang merupakan konstruksi dari pengalaman sehari-hari di jalan.
Corak Mode Kehidupan
Menolak Tetap (Anak) Kecil
Anak jalanan menggunakan tubuhnya sendiri sebagai sarana. untuk ekspresi diri sekaligus sub-versi. Pada tingkat permukaan ditunjukkan perbedaan-perbedaan oleh mereka sekaligus menegaskan pertentangan dengan negara dan masyarakat
sekitarnya (lihat Hebdige, 1979). Tubuh dijadikan sumber produksi dan aktivitas komunikasi dan menjadi lokasi pengetahuan yang krusial bagi komunitas dan hal ini membantu tewrjadinya produksi makna bagi kelompoknya. Melalui pencarian dan tingkah laku yang berbeda itu secara sengaja anak jalanan menolak dan mengejutkan kultur dominannya dengan mensub-versi nilai-nilai utamanya.
Ketika mulai tumbuh lebih besar, menampilkan nilai-nilai kejantanan
merupakan aspek yang vital bagi anak-anak jalanan. Mereka secara teratur mulai berpartisipasi menyusun konstruksi kejantanan dengan mendiskusikan berbagai peran yang dilakukan oleh anak lain serta mengomentari penampilarmya.
Meski secara sosial mereka dikategorikan sebagai anak (kecil), hampir semuanya mengadopsi bentuk-bentuk kedewasaan sebagai tanda pembangkanangan dari harapan-harapan yang ditentukan oleh masyarakat. Mereka memainkan peran yang selama ini dijalankan oleh kaum dewasa yang ada di sekitarnya, menenggak minuman keras, ngepil, judi serta menggemari free sex. Kebiasaan-kebiasaan yang dianggap tidak cocok untuk dilakukan oleh anak justru dianggap mampu membuat mereka merasa tumbuh dewasa dan menjadi jantan.
Judi, misalnya, merupakan permainan yang populer, meski dianggap ilegal dan dimainkan di tempat-tempat tersembunyi. Rata-rata mereka mengaku menikmati permainan judi karena melibatkan resiko dalam pertaruhan, ketrampilan serta konsentrasi dan bila memenangkan permainan, ada rasa bangga menempati posisi puncak dari hasil permainan. Selain itu juga mendapatkan uang yang relatif banyak.
Seorang dewasa yang sering memperhatikan dan bergaul dengan anak-anak jalanan mengatakan bahwa jika dilarang untuk melakukan tindakan tertentu, maka anak-anak jalanan itu seperti disuruh. Apa pun akan dilakukan untuk menentangnya. Katanya, itu bagian dari indentitas pembangkangan. Atau dalam kata lain menolak dianggap (anak) kecil terus.
Gaya Pakaian dan Dandanan Tubuh
Satu kali, H ( 12 tahun) mendapatkan uang cukup banyak dari hasil nyemirnya. Uang itu dibelikan kaos dan celana. jeans. Dengan pakaian baru yang bersih itu kemudian pergi menyemir. Ternyata dengan pakaian bersih semacam itu, tak banyak orang yang mau menyemirkan sepatunya. Berbeda dengan ketika ia memakai pakaian kotor, justru banyak orang yang mau menyemirkan sepatunya. Hal ini menunjukkan adanya satu pertentangan, di satu sisi masyarakat umum menginginkan mereka tampil secara “bersih”, namun bila tampil dengan cara semacam ini maka ia tidak mendapatkan uang yang cukup. Berbeda dengan bila ia menggunakan pakaian kumal, orang tidak menyukai tetapi menghasilkan uang yang cukup.
Situasi semacam itu menyebabkan anak-anak kemudian menggembangkan satu trend cara berpakaian yang cukup khas. Mereka kemudian lebih banyak mengadopsi cara berpakaian dari pengamen dewasa, turis asing atau dari film atau majalah yang dilihat. Salah satu yang cukup populer adalah gaya rasta yang disimbolkan melalui warna merah kuning dan biro dengan simbol daun ganja. Dan simbol itu ditampilkan di tato, di pakaian dan lainnya. Kata mereka rasta cocok dengan anak jalanan. Karena jalanan juga menciptakan orang kaya Bob Marley. Nongkrong di jalan, menghisap ganja, main gitar. Anak jalanan pengin seperti dia. Bukanlah satu hal mengherankan beberapa diantara mereka juga menggunakan model rambut dreadlocks.
Pilihan lain adalah memanjangkan rambutnya. Di Indonesia, rambut panjang merupakan kebalikan dari model rambut para orang tua. Tidak banyak orang tua yang berambut gondrong. Gondrong merupakan citra anak muda. Selain itu dari pihak kemanan gondrong sering diasumsikan sebagai preman. Bila tidak gondrong, sebagian diantaranya justru memilih melicin tandaskan rambutnya. Artinya dari pilihan atas model rambutnya mereka tidak pernah sama dengan yang berlaku dalam masyarakat umum, potongan rambut yang rapi. Dalam kata lain untuk menunjukkan bahwa merekalah yang mengontrol urusan rambut.
Selain rambut, tatto merupakan satu bentuk lain dari cara menampilkan diri. Sebagian anak melawankan tubuh yang bertatto dengan tubuh yang “bersih”. Meski dikalangan umum memiliki tatto disamakan dengan preman, namun dikalangan anak jalanan ia memiliki makna yang berbeda. Beberapa anak mengatakan bahwa tatto merupakan penanda dari “show of force” sekaligus lambang “keras” dan jantan. Sebagian dari mereka membuat tatto sebagai satu tanda untuk menyimpan ingatan tertentu. Beberapa anak membua,t tatto sebagai satu inggatan atas peristiwa perginya seorang volunter ke negara asalnya dan juga peristiwa lain.
Dalam beberapa hal bisa dikatakan bahwa kecenderungan berpakaian atau mentato tubuhnya juga menindik tubuhnya untuk dipasangi anting-anting baik di telingga, alis mata, pusar atau tempat lain tidak bisa dipisahkan dengan relasinya dengan cara penampilan yang normatif. Alternatif yang digunakan oleh anak jalanan tidak bisa tidak berada dalam dikhotomi bersih dan kumal. Menjadi “bersih” bisa jadi justru akan mengancam survival mereka di jalan. Artinya masyarakat dan anak-anak jalanan itu sendiri saling menjaga dengan tegas batas-batas yang mereka inginkan.
(Penyalah)Guna(an) Obat dan Minuman Alkohol
Menenggak minuman keras dan pil adalah satu kebiasaan yang dilakukan selama di jalan. Alasan yang diberikan adalah untuk melupakan masalah. Beberapa studi mengenai anak jalanan secara gamblang menunjukkan berbagai tekanan yang dialami oleh anak jalanan. Secara ekonomi mereka harus bekerja dalam jam kerja yang cukup panjang, secara sosial ia diletakkan sebagai sampah masyarakat, secara hukum keberadaannya melanggar pasal 505 KUHP. Bukanlah satu hal yang mengadaada bila mereka merasa tidak pernah merasa (ny)aman dalam kehidupan sehariharinya.
Tindakan-tindakan yang dipilih ini akan membawa anak-anak pada masalah hukum, karena semua tindakan ini dianggap melanggar hukum. T ( 14) memberikan alasan bahwa sebelum bekerja ia mabuk dulu untuk menghilangkan rasa malu. Karena sebetulnya ia gengsi kalau harus jadi pengamen. Dengan demikian selain sebagai strategi ekonomi, mabuk akhirnya menimbulkan sikap cuek (tidak peduli) dengan aturan hukum.
Secara umum, tindakan semacam ini sering dikatakan sebagai penyalah gunaan obat. Namun demikian, bila di tilik dari sisi lain akan terlihat sebaliknya. Dalam masyarakat modern, dengan mudah dikenali bahwa salah satu jalan keluar untuk mengatasi situasi-situasi yang menekan individu adalah dengan penciptaan obat-obatan. Dengan demikian anak-anak jalanan itu sungguh melakukan satu cara yang sudah disediakan oleh sistem dalam masyarakatnya. Dalam hal ini ia betul-betul memanfaatkan guna obat untuk mengatasi berbagai tekanan yang menimbulkan ketegangan dalam diri. Alat untuk mencapai satu kondisi nyaman.
Musik
Anak-anak juga menggunakan media musik untuk meciptakan ruang bagi dirinya untuk bersuara. Musik digunakan sebagai alat untuk memberdayakan dirinya. Selain untuk mencari makan, bermain musik juga menjadi alat untuk membangun solidaritas. Dalam kesempatan-kesempatan tertentu mereka memainkan musik secara bersama-sama. Dalam kesempatan semacam inilah mereka sering menyuarakan pandangan-pandangan mereka terhadap masyarakat seperti yang tampak dalam syair yang dibuat oleh Dd (14) dan Dw (15):
SAKSI MATA
Suara letusan samar-samar terdengar
Ditengah malam yang pekat
Sesosok tubuh penuh tato
Terbujur kaku di lorong gelapnya kota
Reff: Sejenak jiwanya berteriak
Untuk ungkapkan rasa yang terasa
Dia coba bicara kerryataan Banyak yang melihat
Tak ada saksi mata…
Garis kuning di lengan baju pun puas
Nanyikan lagu kekuasaan
dengan bangga dia melangkah pergi
sambil berharap pangkatnya naik lagi
Reff: Sejenak jiwanya berteriak
Untuk ungkapkan rasa yang terasa
Dia coba bicara keadilan
Dengan pucuk pistol …
Menempel di keningnya.
Secara gamblang syair tersebut merupakan satu kritik terhadap masyarakat yang mengalami rabun ayam terhadap peristiwa yang ada di sekelilingnya. Anak-anak ini menjadi saksi mata atas keseluruhan sisitem masyarakat yang berjalan. Dan untuk bicara seperti itu pun ia sadar ada pistol yang menempel di keningnya, dianggap mengancam atau malah tidak didengar sama sekali.
Kata-kata Akhir
Kehidupan anak jalanan di mulai dengan menanggalkan masa lalunya. Keberadaannya di jalan langsung akan menghadapkan anak-anak ini pelanggaran hukum pasal 505 KUHP sekaligus akan mendapat stempel sampah masyarakat. Dengan demikian kita layak menempatkan tindakan-tindakan yang dipilih anak-anak sebagai satu respon aktif terhadap peminggiran atas dirinya. Seperti yang secara sangat kasar diapaprkan di atas tindakan-tindakan tersebut merupakan kombinasi dari kebutuhan survival, ketetapan hati untuk menentang konformitas kultur dominan, dorongan untuk mendapatkan ke(ny)amanan dan untuk mencapai tujuan-tujuan memperkuat kesetiaan dalam kelompok.
Salah satu strategi yang dipilih adalah cuek dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Dengan menjadi cuek, anak-anak ini berupaya menahan untuk menahan penyingkiran-penyingkran dari dunia sosial sekaligus mengalih ubahkan keberadaannya melalui penciptaan-penciptaan makna. yang spesifik.
Corak moda kehidupan anak jalanan terutama adalah (re)aksi yang sesungguhnya tidak memiliki kekuatan besar, namun dari posisi di pinggiran itu tetap berupaya mengekspresikan dan menciptakan makna bagi dirinya. Dengan menyimpang dari kultur dominannya anak-anak jalanan dengan sekuat tenaganya mempertahankan kontrol atas dirinya sendiri dengan ekspresi “kebebasan” dan simbol kreatifitas sekaligus menjadi ajang dari pertandingan: pemberdayaan atau penaklukan. Pendek kata, bila bagi banyak pihak menjalani kehidupan di jalan diietakkan sebagai “masalah”, maka bagi anak-anak muda itu memilih kehidupan jalanan sebagai satu “solusi”. Paradoks semacam ini memang akan tetap memposisikan anak jalanan di pinggiran, tetapi ia sekaligus juga sumber kekuatan terciptanya satu sub-kultur anak muda perkotaan.
Artikel ini dipresentasikan pada Diskusi dan Pemutaran Video “Subkultur Remaja: Underground, Skuter, PlayStation”, KUNCI Cultural Studies Center- Lembaga Indonesia Perancis, Yogyakarta, 5 Mei 2000.
Ditulis dalam Republish
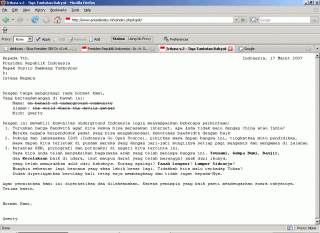 Ada yang lain dalam topik utama di situs Presiden RI. Sebuah surat tuntutan ala tritura tahun 50-an. Komunitas underground menuntut sesuatu dari pemimpin Negara tanpa huru-hara dan demontrasi besar-besaran dengan pengerahan massa. Sebuah tuntutan sederhana dari “pemerhati”. Semangat religi tuntutan 17 Maret 2007 terlihat dari teguran yang disampaikan membawa nuansa nilai keagamaan. Peringatan yang melihat bencana sebagai bentuk teguran dari Absolute Power yang layak untuk diperhatikan. fenomena bencana yang melanda dijadikan satu ukuran peringatan keras (sebuah pemerintahan yang melupakan tanda-tanda langit sampai-sampai dibutuhkan teguran frontal; BENCANA). Harga yang harus dibayar cukup mahal. Ribuan nyawa melayang dan milyaran materi hilang; TIDAK sepenuhnya tergantikan! . tuntutan juga terlihat eksklusif dengan membidik penurunan harga bandwith internet. Kesenjangan social, kesetaraan, keadilan, pemerataan, dan kecemburuan dalam skala global. “pemerhati” memberikan contoh India dan Cina sebagai sebuah Negara yang mampu menfasilitasi kepentingan masyarakatnya (harga bandwith). “masyarakat telematika” mulai unjuk gigi dan TIDAK bisa dianggap remeh.
Ada yang lain dalam topik utama di situs Presiden RI. Sebuah surat tuntutan ala tritura tahun 50-an. Komunitas underground menuntut sesuatu dari pemimpin Negara tanpa huru-hara dan demontrasi besar-besaran dengan pengerahan massa. Sebuah tuntutan sederhana dari “pemerhati”. Semangat religi tuntutan 17 Maret 2007 terlihat dari teguran yang disampaikan membawa nuansa nilai keagamaan. Peringatan yang melihat bencana sebagai bentuk teguran dari Absolute Power yang layak untuk diperhatikan. fenomena bencana yang melanda dijadikan satu ukuran peringatan keras (sebuah pemerintahan yang melupakan tanda-tanda langit sampai-sampai dibutuhkan teguran frontal; BENCANA). Harga yang harus dibayar cukup mahal. Ribuan nyawa melayang dan milyaran materi hilang; TIDAK sepenuhnya tergantikan! . tuntutan juga terlihat eksklusif dengan membidik penurunan harga bandwith internet. Kesenjangan social, kesetaraan, keadilan, pemerataan, dan kecemburuan dalam skala global. “pemerhati” memberikan contoh India dan Cina sebagai sebuah Negara yang mampu menfasilitasi kepentingan masyarakatnya (harga bandwith). “masyarakat telematika” mulai unjuk gigi dan TIDAK bisa dianggap remeh.








